
DESA, ENTITAS DEMOKRASI RIIL
Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara lebih khusus pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan beberapa variabel pengaruh, antara lain: derajat dan kualitas demokrasi, kapasitas (kelembagaan, sumber daya dan organisasi) pemerintahan (Pusat, daerah dan desa), tarik ulur kewenangan otonomi daerah antara pusat-daerah, kesadaran kritis para aktor demokrasi (birokrasi, parlemen, civil society, pers, dan lain-lain), perspektif keterbukaan pemerintahan dan relasi antara state, market serta civil society (negara, pasar dan masyarakat sipil).
Anggapan bahwa pemerintahan desa merupakan penyelenggara pemerintahan pada level “alas kaki”, merupakan pemahaman yang a-historis, reduksionalis dan illogic. Pandangan yang melihat bahwa “otonomi desa” (kini muncul pemahaman yang beragam) merupakan “anugerah” dari tindak karitatif negara, dan bukan kedaulatan asli (genuine) yang melekat pada eksistensi historis entitas yang bernama desa, merupakan kesalahan paradigmatik dan fallacy (cara berpikir) kronis.
Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubu-ngan dengan rakyat. Hal itu menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.
Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen desa dan sebagainya.
Dibandingkan dengan pengaturan pada masa Hindia Belanda tersebut, sangat mengherankan setelah kemerdekaan muncul UU No. 5/1979, yang terbukti mengebiri hak-hak kultural, melakukan penye-ragaman (uniformisasi) dan sentralisasi pengelolaan desa. Akibatnya, desa dalam kurun waktu berlakunya UU tersebut terserap dalam dominasi kekuasaan negara, dan kehilangan ruh demokrasi kerakyatan.
Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa melalui UU No. 22/1999, yang dinilai menghidupkan kembali ruh demokrasi di desa, ternyata tidak dapat berlangsung lama. Berlakunya UU No. 32/2004 yang memundurkan demokrasi di desa menyebabkan ditutupnya kembali katup demokrasi di desa. Spirit demokrasi dalam UU No. 22/1999 yang menghidupkan parlemen desa, telah dipasung oleh UU No. 32/2004. Desa kembali dimaknai sekedar sebagai saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa memiliki daya tawar terhadap berbagai kebijakan negara. Berbagai pemaksaan proyek pusat, distorsi pemberian SLT, penggusuran, dan sebagainya merupakan contoh aktual yang dapat ditunjukkan.
PP No. 72 /2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No. 32/2004, PP itu tidak banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di desa.
Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya dalam PP tentang desa itu, yang pada pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal, pasal 202 ayat (1) UU No. 32/2004 memberikan pengertian pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
Reduksi sistematis terhadap kedudukan dan peranan BPD terlihat sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) hal, yaitu: (1). Tidak ditegaskannya kedudukan BPD sebagai parlemen/legislatif desa; (2). Mekanisme pengisian keanggotaan BPD yang semula dalam UU No. 22/1999 “dipilih” berdasarkan mekanisme demokratis, kini dalam UU No. 32/2004 ditetapkan secara musyawarah dan mufakat dengan basis perwakilan wilayah.
Ditinjau dari sudut aliran pertanggungjawaban (legal accountabi-lity) penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa versi UU No. 32/2004 maupun PP No. 72/2005, terlihat sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2) PP No. 72/2005 menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penye-lenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. Tanggung jawab Kepala Desa kepada BPD hanya dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban, dan kepada masyarakat hanya menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Rumusan aturan dalam pasal 15 ayat (2) PP desa itu tentu saja terlihat kontradiktif dengan pasal 35 huruf b PP desa, yang mengatur bahwa BPD memiliki salah satu wewenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Meskipun pada pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa kepada Bupati/walikota, namun mengacu pada rumusan pasal 15 ayat (2) PP Desa di atas, sangat jelas terlihat ambiguitas pe-ngaturan kewenangan pengawasan BPD.
Selain itu, menyangkut sistem perencanaan di desa terlihat pula belum adanya kehendak negara untuk membangun pola local self planning di desa. Pasal 63 PP Desa masih mengikuti jejak UU No. 32/2004, yang menempatkan perencanaan desa sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, pasal 150 UU No. 32/2004 telah menegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Apabila ditarik garis lurus untuk menghubungkan substansi pengaturan mengenai perencanaan di desa, daerah dan pusat, terlihat sangat jelas yang dibangun adalah model perencanaan terpusat (centralized planning). Sentralisasi perencanaan semacam itu sebenarnya justru mengingkari hakekat otonomi daerah, yang seharusnya terus mengalir menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.
Grand Strategi Implementasi Otonomi Daerah (Dalam Koridor UU No. 32/2004) yang dikeluarkan oleh Depdagri pada tahun 2005, memperlihatkan sangat minimnya komitmen Depdagri untuk menghidupkan kembali hakekat demokrasi desa. Grand Strategi versi Depdagri tersebut lebih banyak memperbincangkan kebijakan otonomi daerah pada level provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan.
Oleh : W. Riawan Tjandra (Dosen FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

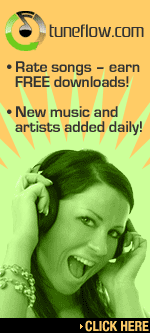

0 comments:
Post a Comment