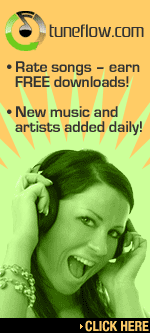Merealisasikan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang
KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
LATAR BELAKANG
Konsepsi peran serta masyarakat, walaupun berbagai pihak telah berkeinginan menetapkannya sejak tahun 80-an, tetapi secara formal baru terwujud konsepsinya di tahun 1992 melalui pengundangan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang di sahkan pada tanggal 13 Oktober 1992. Hal ini juga sebagai upaya mengantisipasi dan menjaga kesinambungan pembangunan. Selanjutnya diikuti oleh Peraturan Pemerintah , pada tanggal 3 Desember 1996, yaitu PP No.69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
Disamping itu pemerintah telah mempersiapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1998 tentang Tatacara Peranserta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah. Dalam perundangan tersebut di amanatkan bahwa untuk penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat. Peran dan keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan dan mengamankan aturan tersebut amat sangat penting artinya karena hasilnya akan dinikmati kembali oleh masyarakat di wilayahnya.
Selanjutnya dengan merujuk pada TAP MPR IV/MPR/2000 tentang rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu “peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreatifitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah” terlihat jelas pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai proses penyelenggaraan pembangunan, termasuk didalamnya dalam proses penataan ruang. Semangat tersebut sejalan dengan bunyi pasal 12 UU No 24 Tahun 1992 bahwa “ Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat” . Prinsip tersebut seiring dengan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1996 yang mengedepankan Pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku atau stakeholder utama pembangunan.
PP No. 69 Tahun 1996 tentang “ Pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam Penataan Ruang ” diatur hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bentuk Peran Serta Masyarakat, Tata Cara Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat diatur berdasar tingkatan hirarki Pemerintahan dari tingkat Nasional, tingkat Propinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Dalam PP ini diatur secara rinci pula hak masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Tidak hanya hak, tetapi diatur pula kewajiban masyarakat dalam proses Penataan ruang.
Peraturan Pemerintah tersebut digagas oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Perekonomian) merangkap sebagai Ketua Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (ditunjuk sebagai koordinator penataan ruang berdasarkan Keputusan Presiden No.62 Tahun 2000 tentang koordinasi penataan ruang nasional) untuk mengatur tata cara pelaksanaannya di Tingkat Pusat. Kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk tata cara pelaksanaan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pada konteks ini difokuskan pada proses perencanaan tata ruang
PEMBANGUNAN MILENIUM ( Millennium Development Goals/MDGs )
Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bulan September 2000, sebanyak 189 negara anggota PBB yang sebagian besar diwakili oleh kepala pemerintahan sepakat untuk mengadopsi Deklarasi Milenium, negara-negara anggota PBB kemudian mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium ( Millennium Development Goals/MDGs ).
Saat ini MDG telah menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, mulai dari tahap perencanaan seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga tahap pelaksanaannya. MDG telah pula menjadi dasar perumusan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di tingkat nasional dan daerah.
Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Indonesia ke depan adalah sebagai berikut:
- Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi,
- Kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah,
- Masih kurang menyatunya kegiatan perlindungan lingkungan hidup dengan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam sehingga sering melahirkan konflik kepentingan antara ekonomi sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dengan lingkungan,
- Kesenjangan pembangunan antar daerah masih lebar, seperti antara Jawa – luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) – Kawasan Timur Indonesia (KTI), serta antara kota – desa,
- Kualitas dan pelayanan infrastruktur yang belum sepenuhnya pulih dan masih tertundanya pembangunan infrastruktur baru,
- Masih adanya potensi aksi separatisme dan konflik horizontal.
Dalam rangka menjawab semua tantangan dalam pembangunan Indonesia 2004-2009, Pemerintah Indonesia menetapkan tiga agenda pembangunan jangka menengah yaitu:
- Menciptakan Indonesia yang aman dan damai,
- Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis,
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Khusus terkait agenda yang ketiga, prioritas pembangunan dan arah kebijakannya adalah sebagai berikut: penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, peningkatan investasi, revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan, pembangunan perdesaan dan pengurangan ketimpangan antar wilayah, peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, pembangunan kependudukan yang berkualitas, dan percepatan pembangunan infrastruktur .
PENATAAN RUANG DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH
Kebijakan sentralisasi pada masa lalu membuat ketergantungan daerah-daerah kepada pusat semakin tinggi dan nyaris mematikan kreatifitas masyarakat beserta seluruh perangkat Pemerintah di daerah. Sementara itu dalam era desentralisasi, partisipasi masyarakat dan azas keterbukaan cenderung untuk dijadikan pedoman dengan asumsi bahwa pelaksanaan prinsip tersebut akan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang ditetapkan dan muncul komitmen untuk melaksanakannya sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan.
Pada posisi lain dengan diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, telah memberikan legitimasi untuk menyerahkan kewenangan dalam proses penyelenggaraan penataan ruang kepada daerah. Konsekuensi dari kondisi tersebut antara lain adalah memberikan kemungkinan banyaknya Kabupaten/Kota yang lebih memikirkan kepentingannya sendiri, tanpa memikirkan sinergi dalam perencanaan tata ruang dan pelaksanaan pembangunan dengan Kabupaten/Kota lainnya untuk sekedar mengejar targetnya dalam lingkup “kacamata” masing-masing.
Untuk mensinergikan kepentingan masing-masing Kabupaten/Kota diperlukan satu dokumen produk penataan ruang yang bisa dijadikan pedoman untuk menangani berbagai masalah lokal, lintas wilayah, dan yang mampu memperkecil kesenjangan antar wilayah yang disusun dengan mengutamakan peran masyarakat secara intensif.
Pada akhirnya, penataan ruang diharapkan dapat mendorong pengembangan wilayah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat ( city as engine of economic growth ) yang berkeadilan sosial ( social justice ) dalam lingkungan hidup yang lestari ( environmentaly sound ) dan berkesinambungan ( sustainability sound ) melalui penataan ruang.
PARADIGMA PENATAAN RUANG
Dalam rangka menerapkan penataan ruang untuk pada akhirnya mewujudkan pengembangan wilayah seperti yang diharapkan, maka terdapat paradigma yang harus dikembangkan sebagai berikut:
- Otonomi Daerah (UU No.22/1999)/( UU 32/2004) , mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembangunan Globalisasi
- Pembangunan wilayah tidak terlepas dari pembangunan dunia, investor akan menanamkan modalnya di daerah yang memiliki kondisi politik yang stabil dan didukung sumberdaya yang memadai
- Pemberdayaan masyarakat
- Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan yang harus dipenuhi Good Governance
- Iklim dan kinerja yang baik dalam pembangunan perlu dijalankan. Karakteristiknya adalah partisipasi masyarakat, transparasi, responsif dan akuntabilitas
STRATEGI PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
Undang-Undang nomor 24 tahun 1992 menyebutkan bahwa ” ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya ”. Selanjutnya, tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Pengertian penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang termasuk didalamnya penataan ruang kota.
Beberapa persoalan dalam penataan ruang adalah:
- Kebijakan Pemerintah yang tidak sepenuhnya berorientasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak terlibat langsung dalam pembangunan.
- Tidak terbukanya para pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan proses penataan ruang ( gap feeling ) yang menganggap masyarakat sekedar obyek pembangunan.
- Rendahnya upaya-upaya pemerintah dalam memberikan informasi tentang akuntabilitas dari program penataan ruang yang diselenggarakan, sehingga masyarakat merasa pembangunan yang dilaksanakan tidak memperhatikan aspirasinya.
- Walaupun pengertian partisipasi masyarakat sudah menjadi kepentingan bersama ( common interest ), akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat pemahaman yang tidak sama. Hal ini ditunjukkan dimana Pemerintah sudah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat, akan tetapi masyarakat merasa tidak cukup hanya dengan proses tersebut. Jadi semua proses keputusan yang diambil harus melibatkan masyarakat.
- Tidak optimalnya kemitraan atau sinergi antara swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan ruang.
- Persoalan yang dihadapi dalam perencanan partisipatif saat ini antara lain panjangnya proses pengambilan keputusan. Jarak antara penyampaian aspirasi hingga jadi keputusan relative jauh. UU 32/2004 (UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000) tentang Otonomi Daerah maka telah menggeser pemahaman dan pengertian banyak pihak tentang usaha pemanfaatan sumber daya alam, terutama asset yang selama ini diangap untuk kepentingan Pemerintahan Pusat dengan segala perizinan dan aturan yang menimbulkan perubahan kewenangan. Perubahan sebagai tanggapan dari ketidak adilan selama ini, seperti perubahan dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak diikuti oleh aturan yang memadai serta tidak diikuti oleh batasan yang jelas dalam menjaga keseimbangan fungsi Regional atau Nasional. Meskipun di dalam UU tersebut desa juga dinyatakan sebagai daerah otonom, namun tidak memiliki kewenangan yang jelas. Dengan kata lain, sebagian besar kebijakan publik, paling rendah masih diputuskan di tingkat kabupaten. Padahal, mungkin masalah yang diputuskan sesunggguhnya cukup diselesaikan di tingkat local/desa. Jauhnya rentang pengambilan keputusan tersebut merupakan potensi terjadinya deviasi, baik yang pada gilirannya menyebabkan banyak kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Berdasar persoalan-persoalan tersebut, upaya keras untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya harus diupayakan. Maka kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (ornop), tokoh masyarakat, dewan perwakilan rakyat, dan pihak-pihak terkait lainnya perlu disinergikan.
TANTANGAN DALAM MENERAPKAN PERENCANAAN PARTISIPATIF MASYARAKAT
Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan partisipatif adalah resistensi birokrasi ( mental block ) dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi. Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan. Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya diserahkan yang akan membawa konsekuensi berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya. Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi “proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi local (kelembagaan partisipasi masyarkat) pun dilaksanakan dengan pendekatan proyek. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang harus ditempuh antara lain: Pemaksaan melalui pembaruan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang lebih prodemokrasi/partisipasi ( structural ); dan pendekatan social-kultural ( mental treatment , pendidikan dan latihan, dsb).
Resistensi politisi diperkirakan akan muncul karena salah satu konsekuensi dari desentralisasi fiscal adalah berkurangnya anggaran daerah yang berarti juga mengurangi nominal anggaran legislative. Hal ini lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan politik dengan mengedepankan sikap kenegarawanan.
Tantangan terberat adalah bagaimana agar manajemen partisipatif ini tidak terdistorsi dan dimanipulasi oleh kelompok tertentu, seperti elit desa dan sebagainya. Karena itu, pengembangan system/mekanisme perumusan/pengambilan kebijakan public, termasuk resolusi konflik, serta peningkatan kapasitas masyarakat dan modal sosial sangat mendesak dilakukan.
Akhirnya, pengembangan manajemen partisipatif ini tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran, keuletan dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkannya.
Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen penting dalam governance maka untuk mendorong terciptanya good governance , banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi awal mewujudkan good governance . Strategi yang diambil organisasi civil society umumnya dilandasi analisis situsasi yang mengemukakan adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik (Hetifah. 2000), yaitu:
- Pertama, hambatan structural yang membuat iklim atau lingkungan menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi fiskal.
- Kedua, adalah hambatan internal masyarakat sendiri, diantaranya kurang inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat kurangnya informasi.
- Ketiga, adalah hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik partisipasi.
UPAYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang untuk mendukung pembangunan wilayah, maka beberapa prinsip dasar yang perlu diperankan oleh pelaksana pembangunan adalah sebagai berikut:
• Menempatkan masyarakat sebagai pelaku yang sangat menentukan dalam proses penataan ruang;
• Memposisikan pemerintah sebagai fasilitator dalam proses penataan ruang;
• Menghormati hak yang dimiliki masyarakat serta menghargai kearifan lokal dan keberagaman sosial budayanya;
• Menjunjung tinggi keterbukaan dengan semangat tetap menegakkan etika dan moral;
• Memperhatikan perkembangan teknologi dan profesional.
Prinsip - prinsip dasar tersebut dimaksudkan agar masyarakat sebagai pihak yang paling terkena akibat dari penataan ruang harus dilindungi dari berbagai tekanan dan paksaan pembangunan yang dilegitimasi oleh birokrasi yang sering tidak dipahaminya. Masyarakat juga bagian dari Rakyat Indonesia yang sudah sepatutnya mendapat perlindungan HAM yang dapat dirumuskan dalam perencanaan tata ruang, seperti hak memiliki rasa aman terhadap keberlanjutan ekonomi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, hak untuk mendapatkan rasa aman terhadap bencana dan lainnya.
Mengacu pada prinsip tersebut sebenarnya telah banyak keterlibatan masyarakat dalam berbagai tingkatan proses pembangunan, termasuk dalam proses Penataan Ruang.
STRATEGI PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
Strategi yang perlu dilakukan dalam mendorong proses partisipasi menuju good government di Indonesia adalah:
a. Peningkatan Kesadaran ( Awareness Raising )
- Memperkaya konsep – konsep pembangungan partisipatoris dalam pengembilan keputusan publik.
- Mendorong kesadaran eksekutif dan legislatitif agar lebih membuka diri terhadap partisipasi masyarakat/warga. Ratusan bahkan ribuan seminar, workshop dan pelatihan telah dilakukan untuk mengangkat aspek partisipasi ke dalam proses pembangunan.
- Mendorong permintaan yang lebih besar untuk partisipasi dan akuntabilitas dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak mereka berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik. Kegiatan utama berupa pendampingan, pelatihan serta kampanye publik.
b. Advokasi Kebijakan ( Policy Advocacy )
- Membangun legal framework berupa kebijakan dan peraturan yang mendorong partisipasi.
- Memberikan insentif/penghargaan terhadap inovasi untuk mendorong partisipasi.
- Mendorong terbentuknya berbagai partnership antara Pemerintah dengan komponen civil society dengan jalan mendesain dan melakukan uji coba proyek – proyek inovatif dan partisipatif.
- Memantau program/proyek pemerintah khususnya yang mengandung komponen partisipasi.
- Mempengaruhi kebijakan dan strategi lembaga – lembaga donor internasional tentang partisipasi dan governance. Caranya antara lain dengan aktif terlibat dalam proses konsultasi yang dilakukan berbagai lembaga donor ketika melakukan policy dan strategi bantuannya. Cara lain adalah melakukan pemantauan proyek pembangunan yang dibiayai lembaga keuangan.
c. Pengembangan Institusi ( Institution Building )
- Mendorong terbentuknya Forum Tata Ruang sebagai wujud konsultasi publik.
- Memperbaiki kualitas partisipasi antara lain dengan menjamin keterlibatan kelompok perempuan dan kelompok marjinal lainnya dalam proses partisipasi
- Memperkuat jaringan antar-NGOs di daerah agar terjadi shared learning antar-institusi sehingga menjadi lebih efektif menjalankan perannya mendorong good governance .
- Memfasilitasi upaya penguatan institusi melalui civil education untuk membangun dan mengembangkan kekuatan serta mengasah keterampilan berpartisipasi secara efektif.
d. Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building )
- Mengembangkan berbagai metode alternatif dan teknik – teknik partisipasi.
- Menyediakan skilled facilitator untuk memfasilitasi proses partisipasi. Pelatihan untuk Community Organiser (CO) dilakukan oleh banyak lembaga untuk mengkader fasilitator – fasilitator handal
- Membangun system informasi dan komunikasi berbagai komunitas ( community based development) .
- Melakukan pelatihan penggunaan metode partisipatoris baik untuk aparat pemerintah, aktivis, LSM maupun masyarakat.
PENUTUP
Pelibatan masyarakat dalam penataan ruang menjadi sangat relevan dalam rangka menciptakan wilayahnya, yaitu tata ruang yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang asri. Berdasarkan pada beberapa hal yang telah diuraikan maka beberapa hal pokok yang terkait Penataan Ruang dalam rangka Pelibatan Masyarakat sebagai berikut:
- Penatan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang mutlak dibutuhkan dalam rangka menjamin hak kepemilikan setiap orang, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial dan mengelola perkembangan pembangunan yang terjadi ( development growth management ).
- Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang tersebut perlu melibatkan masyarakat dengan pendekatan community driven planning . Dengan pendekatan ini diharapkan :
- Terciptanya kesepakatan dan aturan main di masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan sosial disebabkan program penataan ruang yang disusun sesuai dengan aspirasinya.
- Meningkatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program pemanfaatan ruang yang sejalan dengan terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam program penataan ruang.
- Mewujudkan masyarakat mandiri yang dapat memenuhi dan mengupayakan pemenuhan kebutuhannya sendiri seiring dengan proses pembelajaran berpartisipasi yang terkandung dalam pendekatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang.
- Meningkatnya legitimasi program pembangunan Kabupaten/Kota karena disepakati secara bersama-sama yang pada akhirnya dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- Dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam Penataan ruang maka good governance dapat diwujudkan yang pada akhirnya semakin meningkatkan efesiensi dan efektifitas pembangunan wilayah. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pembangunan akan lebih bisa dilakukan secara transparan, akuntabel, bermoral dan beretika yang berorientasi pada rakyat.
Divisi Riset JKPP - Bogor