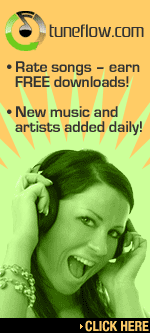Apa hubungan antara otonomi daerah dan kesejahteraan? Mengapa dalam era otonomi daerah sekarang justru kemiskinan sangat merajalela? Sebagaimana dinyatakan Bank Dunia, angka kemiskinan di Indonesia mencakup lebih dari 70 juta jiwa. Lantas apakah berarti otonomi daerah justru berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan?
Sebelum kita meneliti semua itu, setidaknya bisa kita temukan fakta bahwa lahirnya otonomi daerah di Indonesia lebih karena perubahan kondisi politik daripada alasan paradikmatik-empirik. Tahun 1998, masyarakat Indonesia merasakan kemuakan atas pemerintahan yang sangat sentralistis dan ingin menuju pola masyarakat yang lebih menjanjikan kebebasan. Realitasnya, setelah masyarakat Indonesia berada dalam era otonomi daerah, berbagai problem bermunculan dan implemenasi atas konsep otonomi itu memunculkan banyak konflik baik vertikal maupun horizontal.
Empat Problem Otonomi Daerah
Pertama, pudarnya negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemimpin negara adalah atasan para pemimpin di bawahnya. Namun di Indonesia, apakah faktanya memang demikian? Kenyataannya sangat jauh dari itu. Bagaimanapun para gubernur, bupati, dan walikota untuk terpilih butuh dukungan partai-partai. Realitas ini membuat mereka lebih taat pada pimpinan partai yang mendukung mereka. Undangan pertemuan pemerintah di atasnya sering diabaikan, sementara undangan pimpinan partai ditanggapi segera, bahkan cepat-cepat berangkat dengan memakai uang negara. Ini membuat Indonesia seperti mempunyai banyak presiden. Walaupun para pimpinan partai tidak memerintah, tapi mereka mengendalikan para gubernur dan kepala daerah yang didukung partai mereka.
Kedua, lemahnya jalur komando. Dalam konsep otonomi daerah, para gubernur bukan atasan bupati/walikota. Sementara pemerintah pusat membawahi daerah yang jumlahnya lebih dari empat ratus buah. Di sisi lain, gubernur juga merupakan jabatan politis yang untuk meraihnya membutuhkan dukungan politik partai. Seringkali yang terjadi presiden, gubernur, dan bupati/walikota berasal dari partai yang berbeda. Kiranya, adalah wajar kalau dengan semua itu jalur komando dari pusat ke daerah menjadi terputus. Kemampuan pusat hanyalah mengkoordinasikan seluruh pemerintahan di bawahnya, itupun dalam tingkat koordinasi yang sangat lemah.
Ini mengakibatkan program-program pemerintah pusat tidak berjalan, padahal banyak program yang sangat penting demi keselamatan rakyat. Alasan Menkes Siti Fadilah Supari terkait kegagalam penanganan flu burung, dimana instruksi dan dana dari departemen kesehatan tidak mengalir ke sasaran karena para kepala daerah tidak mempedulikan (sehingga banyak korban berjatuhan), kiranya cukup relevan sebagai contoh. Realitasnya NKRI sekarang telah tiada. Yang ada hanyalah persekutuan ratusan kabupaten dan kota di Indonesia.
Ketiga, semakin kuatnya konglomeratokrasi. Putusnya jalur komando dalam pemerintahan di Indonesia terasa sangat ironis jika melihat kekuatan komando di partai dan perusahaan. Partai dan perusahaan umumnya bersifat sentralistis. Pimpinan pusat bagaimanapun juga adalah atasan pimpinan di tingkat provinsi. Dan pimpinan tingkat provinsi adalah atasan pimpinan tingkat daerah. Ini membuat partai dan perusahaan di Indonesia jauh lebih solid daripada pemerintah. Partai dan perusahaan lebih terasa sebagai suatu “pihak”. Ini lain dengan pemerintah yang lebih terasa sebagai “kumpulan” atau bahkan sekedar “tempat persaingan”. Dengan melihat bahwa pemerintahan di Indonesia terpecah-pecah, pemimpin pemerintahan butuh dukungan partai, dan partai butuh dana yang umumnya mengandalkan dukungan para konglomerat, maka bisa disimpulkan bahwa konglomerat merupakan subjek atas partai dan partai merupakan subjek atas pemerintah. Ini berarti yang berkuasa di Indonesia adalah para konglomerat.
Realitas ini semakin terasa parahnya jika mengingat bahwa Indonesia sangat tergantung modal asing dan bahwa kekuatan korporasi di dunia saat ini di atas negara (sebagaimana dinyatakan Prof. Hertz, dari 100 pemegang kekayaan terbesar di dunia sekarang 49-nya adalah negara, sementara 51-nya perusahaan; kekayaan Warren Buffet, orang terkaya di dunia, di atas APBN Indonesia). Bisa dibayangkan jika di jaman dulu puluhan kerajaan dengan kondisi politiknya yang “mungkin terpecah” bisa dikuasai oleh VOC (sebuah perusahaan dunia), bagaimana sekarang ratusan daerah yang umumnya secara politis “sudah terpecah” menghadapi puluhan VOC baru yang kekuatannya di atas negara? Dari fakta ini saja sangat bisa dipahami mengapa Indonesia berada dalam cengkeraman korporatokrasi/konglomeratokrasi.
Keempat, terabaikannya urusan rakyat. Asumsi yang diberlakukan dalam konsep otonomi daerah adalah rakyat bisa mengurus dirinya sendiri. Pelaksanaan asumsi ini adalah bahwa para gubernur, bupati, dan walikota, walaupun tidak dalam komando pemerintah pusat, tetapi dalam kontrol DPRD setempat. Sayangnya, bagaimanapun juga DPRD mempunyai realitas yang sama dengan para pimpinan pemerintahan dalam hubungannya dengan partai dan korporasi/konglomerat. Ini berarti kekuasaan korporasi justru semakin mengakar.
Realitas ini bisa dilihat dari fakta bahwa berbagai parameter keberhasilan adalah ukuran korporasi, bukan ukuran kesejahteraan rakyat. Padahal, seringkali hitungan korporasi tidak sesuai dengan hitungan kesejahteraan. Dengan ukuran pendapatan per kapita (angka yang dibutuhkan korporasi), banyak kabupaten di Indonesia mempunyai pendapatan per kapita di atas Rp.18 juta per tahun (Rp. 1,5 juta/bulan atau Rp. 6 juta / keluarga). Itu berarti banyak keluarga di Indonesia yang mempunyai penghasilan di atas keluarga doktor. Kenyataannya, lebih 70 juta lebih rakyat miskin (angka kemiskinan merupakan hitungan kesejahteraan). Indonesia memang negeri yang sangat aneh. Berbagai bentuk iklan semakin megah dan meriah. Tapi jalan-jalan semakin berlubang.
Kiranya, empat problem di atas sudah bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara otonomi daerah dengan munculnya berbagai problem di Indonesia. Dengan otonomi, harapannya adalah suasana yang lebih bebas dan desentrlistis. Kenyataannya, sentralisasi lama dipreteli kekuasaannya untuk masuk sentralisasi baru, yaitu kekuasaan korporasi/konglomerasi internasional.
Solusi Syariah
Selain konsep otonomi daerah, alternatif solusi lain yang dalam dekade terakhir mulai menjadi bahasan banyak pihak untuk memperbaiki kesejahteraan negeri ini adalah konsep ekonomi syariah. Hanya saja, sebenarnya kita perlu membahasnya secara lebih makro, yaitu solusi syariah secara makro untuk negara. Selain terasa janggal jika rakyat Indonesia yang mayoritas muslim tidak pernah mencoba membahas tentang solusi syariah, solusi syariah sendiri secara paradikmatik-empirik mempunyai beberapa kekuatan. Solusi syariah secara makro juga mempunyai pandangan khas tentang desentralisasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi kebijakan negara berdasar solusi syariah.
1. Sentralisasi Politik
Selama ini orang umumnya trauma jika berbicara tentang sentralisasi. Semua itu bisa dipahami jika mengingat sentralisasi di jaman Soeharto (Orde Baru). Namun sentralisasi dalam syariah cukup berbeda dengan sentralisasi orde baru. Sentralisasi orde baru cukup ekstrim. Pemerintah pusat bukan hanya merupakan atasan pemerintahan di bawahnya. Tapi juga mempreteli kekuasaan di bawahnya dan mencengkeram dengan sangat kuat berbagai bidang operasional daerah dengan berbagai departemennya. Sentralisasi dalam syariah lebih menekankan agar negara berada dalam satu kesatuan politik. Ini dilakukan dengan cara khalifah (kepala negara) mempunyai akses komando atas pemerintahan di bawahnya, berhak mengangkatnya, dan berhak memberhentikannya. Sedangkan kekuasaan yang langsung dipegang pemerintah pusat itu sendiri lebih pada kekuasaan yang tidak bersifat operasional dan administratif, seperti militer, kepolisian, luar negeri, ekonomi kebijakan, dan keuangan.
Dalam pemerintahan Islam biasa dikenal wali zakat dan wali sholat. Wali zakat adalah gubernur keuangan dalam tiap-tiap provinsi, yang menjadi saluran input keuangan dari daerah ke pusat. Sementara wali sholat adalah gubernur sebagaimana dalam pengertian sekarang, yang memikirkan urusan rakyat dengan anggaran yang dibutuhkan –- hanya saja dalam Islam anggaran meminta ke pusat sesuai kebutuhannya. Ini berarti sektor input dan output keuangan berada dalam jalur yang berbeda. Kondisi ini diharapkan akan menguntungkan daerah dalam beberapa hal: komando pusat, anggaran yang jelas, lebih bersih dari politisasi dalam amsalah operasional, dan lebih terjaga dari korupsi. Bagi negara secara keseluruhan lebih utuh secara politik.
2. Kontrol Pemerintahan yang Sehat
Gambaran pemerintahan dengan strukur pohon di atas barangkali memunculkan kekhawatiran. Yaitu: kesewenang-wenangan pemerintah pusat dan kurangnya partisipasi publik dan partisipasi daerah. Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan fakta bahwa syariah lebih menekankan agar pemerintah pusat dikontrol, bukan dipreteli kekuasaannya. Beberapa hal yang disiapkan syariah untuk menciptakan kondisi ini adalah: 1) Larangan memberhentikan mahkamah mazhalim (pimpinan peradilan negara) ketika sudah mendapat aduan tentang pemerintah; 2) Anggota majelis umat (dewan perwalikan) dipilih langsung oleh rakyat; 3) Majelis Umat terdapat di pusat, provinsi,dan daerah. Mereka merupakan lembaga kontrol dan masukan; 4) Partai politik bebas berdiri sepanjang berdasarkan syariah Islam, tugasnya bukan mencari kedudukan tapi mengontrol pemerintahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Jadi, berdasar syariah pemerintah pusat “dipaksa kuat, tapi juga dijaga supaya waras”. Kondisi ini juga lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk “mempunyai pemerintahan yang baik”, bukannya “ingin memerintah sendiri”.
3. Desentralisasi Administrasi
Sungguhpun berlaku sentralisasi politik, tapi administrasi terdesentralisasi. Berbagai bidang operasional seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan kebutuhan publik menjadi tanggung jawab daerah. Dengan melihat fakta bahwa daerah tidak menjadi jalur input keuangan tapi jalur output pelayanan, maka rakyat akan merasakan manfaat desentralisasi. Desentralisasi tidak akan dirasakan sebagai “naiknya karcis parkir” dan “melambungnya pajak” seperti saat ini. Desentralisasi akan dirasakan sebagai kecepatan dalam pelayanan.
4. Orientasi Pemerataan
Berbeda dengan sistem ekonomi yang ada sekarang yang menganggap masalah ekonomi adalah kelangkaan, penanganan kelangkaan butuh produksi, pelaksanaan produksi butuh korporasi, kelancaran korporasi butuh peran pemerintah sebagai fasilitator korporasi; sistem ekonomi Islam mempunyai filosofi berbeda. Sistem ekonomi Islam berdasarkan filosofi tersendiri, yaitu masalah ekonomi adalah kurangnya distribusi, pelaksanaan distribusi butuh peran negara, peran negara butuh kebijakan yang adil, kebijakan yang adil butuh rujukan syariah. Kenyataannya, syariah memang sangat mengatur masalah distribusi: 1) Zakat untuk mengembalikan fakir, miskin, dan gharim (penghutang) kembali ke titik nol; 2) Seluruh sumber daya alam adalah milik umat dan dipakai untuk sesejahteraan umat sedangkan negara sekedar pengelola; 3) Kebijakan agraria yang sangat melindungi petani, seperti larangan menganggurkan tanah tiga tahun, penyitaan negara atas tanah yang dianggurkan, serta kebolehan memagari tanah kosong.
Sedikit contoh paradigma syariah Islam dalam kehidupan bernegara itu kiranya bisa menjadi pertimbangan baru untuk mengambil langkah yang tepat untuk negeri ini.
Sumber: http://jurnal-ekonomi.org